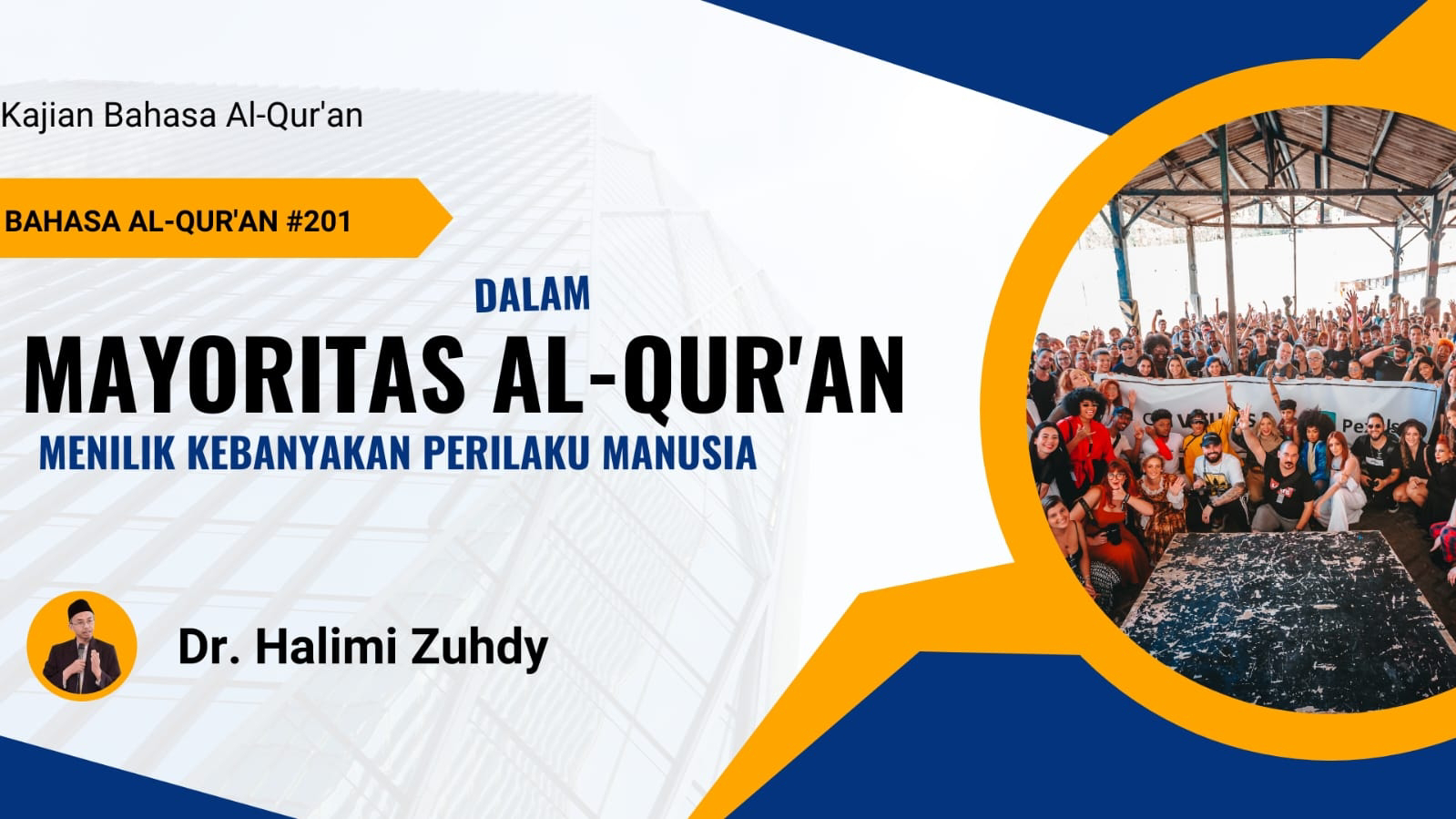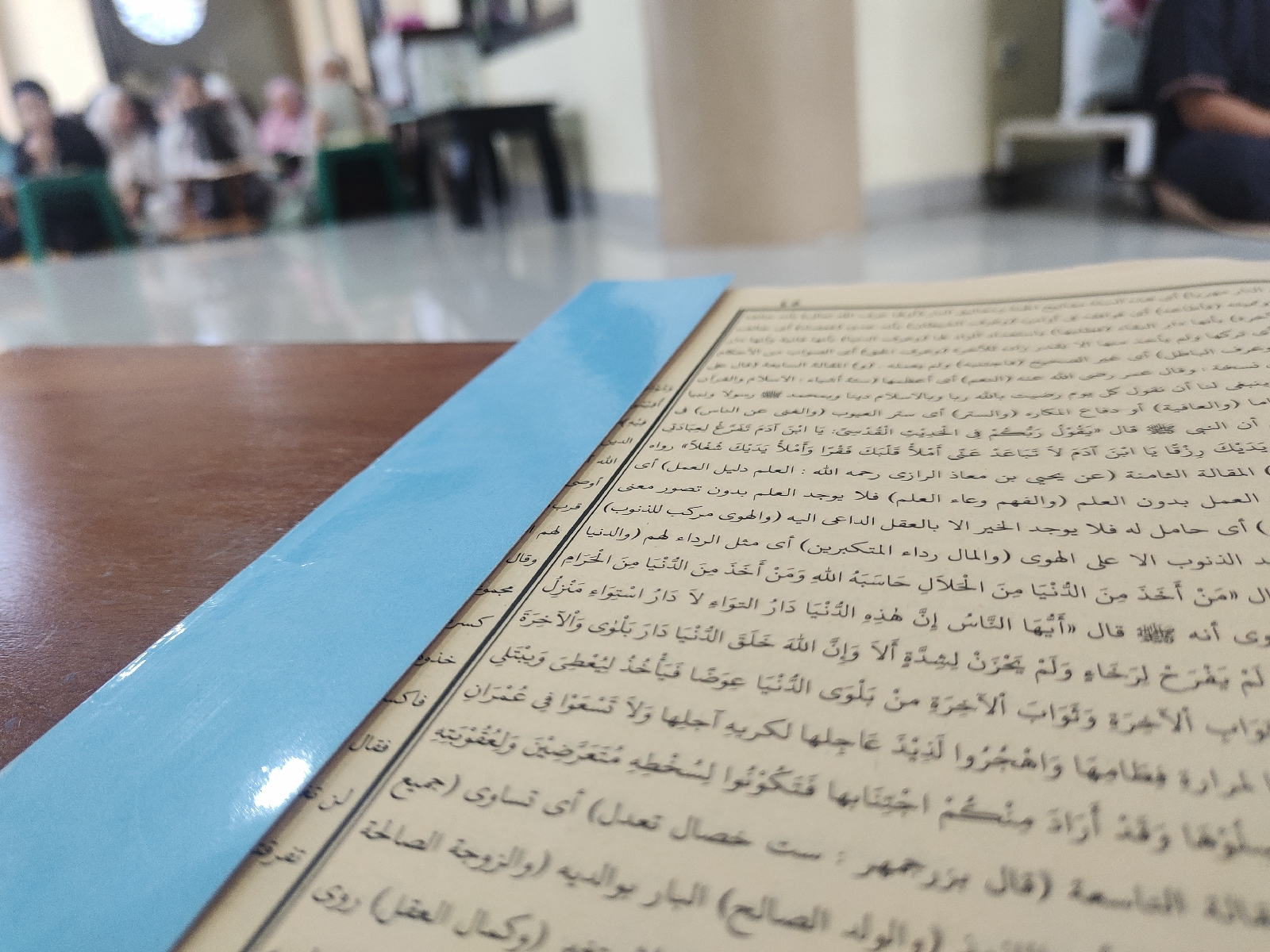Halimi Zuhdy
Pagi tadi saat membaca Surat Al-Kahfi bersama jamaah di Masjid Baiturrahman, saya terpaku pada satu Ayat:
وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا
Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah — QS. Al-Kahfi: 54.
Ayat ini terasa hidup di tengah hiruk-pikuk media sosial kita hari ini. Perdebatan tak kunjung padam. Ada yang membangun keindahan, memotivasi, berbagi kebaikan, tapi tak sedikit yang hanya menebar permusuhan dan caci maki. Berdebat tanpa ujung, berakhir persaudaraan yang hancur. Maka saya pun menelusuri lebih dalam: bagaimana Al-Qur’an menggambarkan “الأكثرية” (mayoritas, kebanyakan)?
Dalam Al-Qur'an, terdapat kata yang menunjukkan pada makna "banyak, berlimpah, kebanyakan" dan derivasinya. Kurang lebih ada 90 kata. Terdapat beberapa lafaz yang memiliki akar makna yang sama, yaitu menunjukkan makna banyak atau berlimpah, seperti جم (banyak), غدق (melimpah ruah), لبد (berkerumun atau menumpuk), dan كثر (banyak atau banyak jumlahnya). Meskipun berasal dari makna dasar yang serupa, masing-masing lafaz ini memiliki nuansa makna tersendiri yang membedakannya dalam konteks penggunaannya.
Ternyata, dalam banyak Ayat, dengan penggunaan "al-aktsar, mayoritas, kebanyakan" manusia digambarkan dengan karakter yang negatif. Berikut beberapa contohnya:
1. Mayoritas tidak beriman
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ
Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukan-Nya — Yusuf: 106.
وَمَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya— Yusuf: 103.
2. Mayoritas tidak tahu
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui— Al-A’raf: 187.
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui — An-Nahl: 75.
3. Mayoritas tidak bersyukur
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ
Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur— Al-Baqarah: 243.
4. Mayoritas Kafir
فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
Tetapi kebanyakan manusia tidak menghendaki kecuali kekafiran) — Al-Furqan: 50.
5. Mayoritas tidak menggunakan akal
قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
Katakanlah: "Segala puji bagi Allah", tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti) — Al-Ankabut: 63.
Fenomena ini bukan hanya data statistik spiritual, tapi juga realitas sosial. Al-Qur’an sedang memperingatkan kita: jangan terlalu terpesona dengan suara mayoritas. Yang ramai belum tentu benar. Yang viral belum tentu berakhlak dan baik. Bahkan dalam konteks dakwah, Allah mengingatkan:
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ
Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah — Al-An’am: 116.
Sebaliknya, Al-Qur’an justru memuji mereka yang sedikit, namun kokoh:
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ
Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur— Saba’: 13.
Kita hidup di zaman debat tanpa ujung. Ayat tentang “manusia paling banyak membantah, berdebat” seakan menyingkap tabir sosial kita hari ini. Maka marilah kita bercermin: apakah kita termasuk “yang banyak”, atau berjuang untuk menjadi “yang sedikit”? Karena dalam ukuran Al-Qur’an, kebenaran bukan ditentukan oleh kuantitas, tapi oleh kualitas iman, ilmu, dan syukur. Dan belum tentu yang sedikit benar lo ya?! Jangan disalah pahami. Lihat konteksnya.
Al-Qur’an, melalui penyebutan sifat-sifat negatif yang sering dikaitkan dengan kelompok mayoritas (al-aktsariyyah), tidak sekadar menginformasikan kondisi manusia, tetapi mengungkap hakikat jiwa manusia di setiap waktu dan tempat. Jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu, lalai, ingkar, dan terpaut pada syahwat duniawi. Karena itu, Al-Qur’an hadir untuk mengarahkan manusia agar melawan kecenderungan-kecenderungan negatif tersebut, menahan syahwatnya, serta memperbanyak zikir dan syukur kepada Allah. Dengan demikian, manusia diajak untuk tidak larut dalam arus mayoritas yang menyimpang, melainkan membangun kesadaran pribadi yang menuntunnya pada jalan kebenaran.
Namun, Ayat-Ayat yang mencela mayoritas (al-aktsariyyah) harus dibaca dalam konteksnya masing-masing dan dipahami berdasarkan sebab turunnya. Sebab, sebagian besar Ayat-Ayat tersebut merujuk pada kelompok tertentu, seperti kaum musyrik atau Bani Israil, sehingga celaan terhadap mayoritas tidak berlaku secara mutlak. Meski demikian, terdapat juga beberapa Ayat yang menyifati mayoritas dengan sifat tercela secara umum, seperti tidak mengetahui, tidak bersyukur, dan tidak berpikir. Dalam hal ini, konteks dan susunan Ayat menjadi faktor utama dalam memahami maksud dari ayat tersebut, sehingga penting untuk memperhatikan konteks agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami pesan Al-Qur’an.
Asyik kan?
Ayo ikuti kajian berikutnya tentang siapakah yang sedikit, minoritas atau paling sedikit dalam Al-Qur'an. Dan juga mengapa Al-Qur'an menggunakan kata "katsirun"?
Malang, 11 April 2025
Maraji':
Al-Qur'an Al-Karim
Tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tahrir wattanwir, Al-Alusi, Al-Muharrir Al-wajiz.
Kajian-kajian Al-Qur'an, Mukjizat Al-Quran, Balaghah, Sastra Arab, Turast Islamiyah, Keagamaan, Kajian Bahasa dan asal Muasal Bahasa, dan lainnya.
🧷 *Fatwa Cinta* _(Saluran WA)_
🌎 www.halimizuhdy. com
🎞️ YouTube *Lil Jamik*
📲 Facebook *Halimi Zuhdy*
📷 IG *Halimizuhdy3011*
🐦 Twitter *Halimi Zuhdy*
🎼 TikTok *HalimiZuhdy*