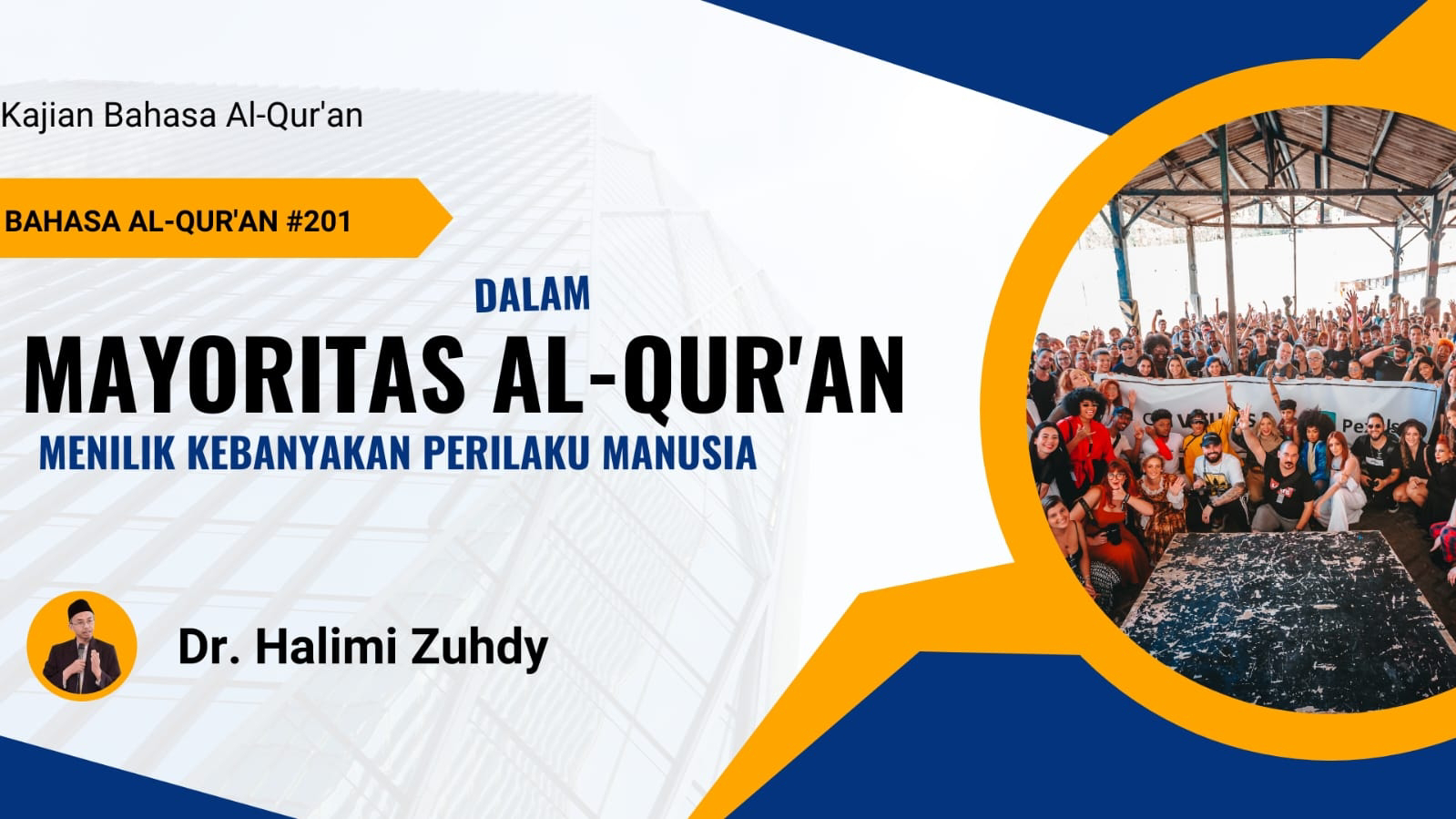“
Halimi Zuhdy
Setelah saya menulis tentang "Kyai Tidak Memihak orang Desa?" dan "Fatwa vs Petuah", kok ingin menulis tetang "fiqih", "fahm", "faqih", "fahim" dan beberapa hal terkait denga pemahaman teks agama. Mengapa? Karena tidak sedikit yang merasa paham, tidak benar-benar paham. Ada yang dianggap benar-benar paham (teks agama, dalil dll), tapi, tidak mengerti maksudnya. Maka, dalam hal ini ada istilah "ikhtilaf darajatil ulama fi fahm wal fiqhi". Bahasanya Gus Rijal Mumazziq Z, berbeda antara al-faqih wal mutafaqqih. Sebelum ke persoalan yang lebih rumit; fiqih dan fahm. Ada yang sebenarnya "derajat pendengaran yang kadang lupa dipahami. He.
Di tengah hiruk pikuk persoalan per-Horegan, kita sering kali hanya “mendengar” hukum haram tanpa benar-benar memahami maksud-nya. Bahkan, yang menolak mentah-mentah tidak membaca teks keharamannya. Ini perbedaan tahu, mengerti, paham, dan istilah lainnya. Dan istilah dalam bahasa Arab tambah rumit dan banyak sekali. Coba, kita mulai dari pemahaman kata "mendengar" dalam Al-Qur'an. Karena persoalan Horeg, adalah persoalan kuping🤣telinga dan udzun.
Lah, ada yang hanya sering “mendengar” tanpa benar-benar mendengarkan. Suara masuk ke telinga, tetapi hati tetap tertutup. Dalam Al-Qur’an, kata السَّمْع/as-sam‘/mendengar bukan sekadar fungsi biologis, melainkan sebuah proses kesadaran. Ia menjadi gerbang bagi manusia untuk memahami kebenaran.
Menariknya, Al-Qur’an tidak hanya menyebut satu istilah untuk mendengar, tetapi membedakannya dalam empat tingkatan: السَّمْع/sam‘, الاستماع/istima‘, الإصغاء/ishgha‘, dan الإنصات/insat. Perbedaan ini bukan hanya soal kata sajo, tapi menggambarkan kedalaman sikap batin terhadap apa yang kita dengar.
Tingkatan pertama adalah السمع/sam‘, yakni sekadar mendengar suara tanpa memahami maknanya. Al-Qur’an mengibaratkan orang kafir seperti ternak yang hanya mendengar panggilan tanpa mengerti maksudnya (QS. Al-Baqarah: 171). Ini bukan sekadar perumpamaan, tetapi kritik tajam terhadap mereka yang telinganya berfungsi, tetapi hatinya tertutup.
Berikutnya adalah الاستماع/istima'. Berbeda dengan sam‘ dan istima‘ adalah mendengar dengan kesadaran, fokus, dan niat mengambil pelajaran. Kata ini dipakai ketika Al-Qur’an menceritakan sekelompok jin yang datang “mendengarkan (يستمعون) Al-Qur’an” (QS. Al-Ahqaf: 29). Ada usaha, ada perhatian, ada keseriusan untuk memahami.
Berikutnya, yang ketiga adalah الإصغاء/Ishgha‘ adalah mendengar yang melibatkan hati. Ini bukan sekadar soal telinga, tetapi bagaimana suara itu menyentuh batin. Menariknya, kata صغت قلوبكما dalam QS. At-Tahrim: 4 memiliki akar kata yang sama dengan ishgha‘, menunjukkan bahwa mendengar yang sejati lahir dari hati yang jernih. Ini, agak rumit juga. Tapi, mudah dipahami.
Terrahkhir adalah الإنصات/Inshat berarti diam dan memberikan perhatian penuh. Saat Al-Qur’an dibacakan, Allah memerintahkan: “Dengarkanlah (فاستمعوا) dan diamlah (أنصتوا), agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-A‘raf: 204). Ini adalah bentuk mendengar yang disertai penghormatan, bukan sekadar proses fisik. Bisa dilihat di vedio YT Lil Jamik (lebih lengkap)
Al-Qur’an berkali-kali menyebut bahwa pendengaran erat kaitannya dengan hati. Jika hati tertutup, telinga seolah-olah ikut tuli. Dalam QS. Al-An‘am: 25 disebutkan:
{ وَمِنۡهُم مَّن یَسۡتَمِعُ إِلَیۡكَۖ وَجَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن یَفۡقَهُوهُ وَفِیۤ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرࣰاۚ وَإِن یَرَوۡا۟ كُلَّ ءَایَةࣲ لَّا یُؤۡمِنُوا۟ بِهَاۖ حَتَّىٰۤ إِذَا جَاۤءُوكَ یُجَـٰدِلُونَكَ یَقُولُ ٱلَّذِینَ كَفَرُوۤا۟ إِنۡ هَـٰذَاۤ إِلَّاۤ أَسَـٰطِیرُ ٱلۡأَوَّلِینَ }
Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu (Muhammad), dan Kami telah menjadikan hati mereka tertutup (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, “Ini (Al-Qur`ān) tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu.” Para mufasir seperti Al-Tabari menegaskan bahwa hati yang keras ibarat telinga yang tak lagi berguna. Orang seperti ini bukan tidak bisa mendengar, tetapi tidak mau mendengarkan.
Al-Qur’an menggambarkan pendengaran sebagai salah satu bentuk kenikmatan di akhirat. Orang beriman hanya akan mendengar salam dan ucapan damai (QS. Al-Waqi‘ah: 25-26). Sebaliknya, orang kafir yang menutup telinga di dunia akan merasakan kebisuan telinga di akhirat (QS. Al-Anbiya: 100).
Mengapa Pendengaran Disebut Lebih Dahulu?
Penelitian modern menunjukkan bahwa indra pendengaran adalah yang pertama berkembang pada janin, lebih awal daripada penglihatan. Fakta ini selaras dengan urutan penyebutan dalam Al-Qur’an yang sering mendahulukan kata السَّمْع/as-sma (pendengaran) daripada البصر/al-bashar (penglihatan). Ini bukan kebetulan, tetapi ketelian bahasa Al-Qur'an. Diqqah balighah.
Allhu'alam bishawab
Surakarta, 22 Juli 2025